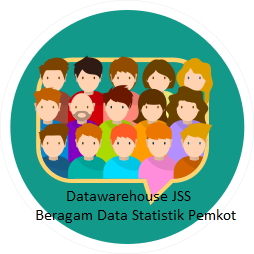Sejarah
12.304xAntara Yogyakarta, Tegalrejo dan Diponegoro
Sejarah Kota Yogyakarta
Pembentukan wilayah Yogyakarta dimulai saat adanya Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari tahun 1755 yang memisahkan wilayah Mataram menjadi 2 bagian, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Sejarah Perjanjian Giyanti bermula dari konflik yang terjadi di Kerajaan Mataram. Konflik bermula dari pertikaian tiga calon pewaris Kerajaan Mataram, yaitu Pangeran Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa.
Perjanjian Giyanti adalah sebuah perjanjian antara VOC di bawah tanda tangan Gubernur Nicholas Hartingh atas nama Gubernur Jendral Jacob Mossel, pihak Kerajaan Mataram yang diwakili oleh Pakubuwana III dan Pangeran Mangkubumi sebagai siasat VOC memecah belah Kerajaan Mataram.
Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, babak awal Kasultanan Yogyakarta dimulai. Pada Kemis Pon, 13 Maret 1755 (29 Jumadilawal 1680 TJ) Pangeran Mangkubumi dinobatkan sebagai raja pertama Ngayogyakarta Hadiningrat dengan gelar Sri Sultan Hamengku Buwono I (Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Alega Abdul Rachman Sayidin Panatagama Khalifatullah).
Pangeran Mangkubumi segera menetapkan bahwa daerah Mataram yang ada di dalam kekuasaannya itu diberi nama Ngayogyakarta Hadiningrat dan beribukota di Ngayogyakarta (Yogyakarta).
Tempat yang dipilih sebagai pusat pemerintahan dan ibukota Ngayogyakarta (Yogyakarta) adalah Hutan Beringin yang memiliki batas-batas alam berupa Kali Code di sebelah timur dan Kali Winongo di sebelah barat. Di sebelah utara dibatasi oleh Gunung Merapi, sementara di selatan berbatasan dengan pantai Laut Selatan.
Lokasi ini dianggap strategis berdasar letak dan keadaan lahan agar berpotensi menyejahterakan dan memberi keamanan untuk penduduk Yogyakarta.
Di Hutan Beringin terdapat sebuah desa kecil bernama Pachetokan, dan didalamnya terdapat suatu pesanggrahan bernama Garjitowati. Pesanggarahan ini dahulu dibuat oleh Susuhunan Paku Buwono II dan kemudian namanya kemudian diubah menjadi Ayodya. Setelah penetapan tersebut diatas diumumkan, Sultan Hamengku Buwono segera memerintahkan kepada rakyat membabad hutan Beringin untuk didirikan Kraton.
Selama pembangunan Kraton tersebut, Sultan Hamengku Buwono I berkenan menempati pasanggrahan Ambarketawang di daerah Gamping, yang juga tengah dibangun. Dari tempat inilah beliau selalu mengawasi dan mengatur pembangunan kraton.
Setahun kemudian, Sultan Hamengku Buwono I berkenan memasuki Istana Baru sebagai peresmiannya. Dengan demikian berdirilah Kota Yogyakarta atau dengan nama utuhnya ialah Negari Ngayogyakarta Hadiningrat. Pesanggrahan Ambarketawang selanjutnya ditinggalkan oleh Sultan Hamengku Buwono untuk berpindah menetap di Kraton yang baru. Kejadian ini terjadi tanggal 7 Oktober 1756 sehingga tanggal 7 Oktober ditetapkan sebagai Hari Ulang Tahun Kota Yogyakarta.
Tegalrejo dan Diponegoro
Tegalrejo menjadi salah satu wilayah yang berada di daerah Yogyakarta. Tepatnya berada di sebelah barat laut kraton Yogyakarta dan terletak diantara Sungai Winongo dan Sungai Code. Pada awalnya, tlatah Tegalrejo ini dulu terlantar hingga permaisuri Sultan HB I yaitu Kanjeng Gusti Ratu Ageng pada 1790 (saat putranya bertahta sebagai Sultan HB II) menyatakan keluar dari kraton dan mesanggrah di Ndalem Tegalrejo. Beliau menyatakan keluar dari kraton karena sering berselisih dengan anaknya dan merasa kecewa sehingga membuka lahan baru di barat laut kraton.
Seperti yang dituturkan Tembang Sinom dalam Babad Diponegoro berbunyi :
"Kanjeng Ratu Geng winarni/pan asring selaya neki/lan kang putra pribadi/dadya mutung adhudhukuh/babat kang ara-ara/mapan lajeng den dalemi…"
(Perihal Ratu Ageng/betapa sering beliau berselisih/dengan putranya sendiri/maka ia kecewa lalu pergi/membuka lahan baru/tanah-tanah terlantar digarapnya/lantas menetap tinggal di sana…)
Daerah yang dibuka dan digarap oleh Kanjeng Gusti Ratu Ageng beserta pengikutnya kemudian menjadi daerah subur dan menjadi pusat pendidikan agama Islam. Sehingga banyak orang yang kemudian menetap di daerah itu. Selanjutnya daerah itu disebut Tegalrejo (tegal=lahan, rejo=ramai).
Ratu Ageng Tegalrejo juga mengasuh cicitnya yang bernama Raden Mas Ontowiryo (Pangeran Diponegoro) yang merupakan putra Sultan HB III.
Sosok Pangeran Diponegoro dikenal secara luas karena memimpin Perang Diponegoro atau disebut sebagai Perang Jawa karena terjadi di tanah Jawa. Perang ini merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara pada tahun 1825 hingga 1830.
Perang tersebut terjadi karena Pangeran Diponegoro tidak menyetujui campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan. Selain itu, sejak tahun 1821 para petani lokal menderita akibat penyalahgunaan penyewaan tanah oleh warga Belanda, Inggris, Prancis, dan Jerman.
Gubernur-Jenderal Hindia-Belanda saat itu, Van der Capellen mengeluarkan dekrit pada tanggal 6 Mei 1823 yang menyatakan bahwa semua tanah yang disewa orang Eropa dan Tionghoa wajib dikembalikan kepada pemiliknya per 31 Januari 1824. Namun, pemilik lahan diwajibkan memberikan kompensasi kepada penyewa lahan Eropa.
Pangeran Diponegoro membulatkan tekad untuk melakukan perlawanan dengan membatalkan pajak Puwasa agar para petani di Tegalrejo dapat membeli senjata dan makanan. Kekecewaan Pangeran Diponegoro juga semakin memuncak ketika Patih Danureja atas perintah Belanda memasang tonggak-tonggak untuk membuat rel kereta api melewati makam leluhurnya. Beliau kemudian bertekad melawan Belanda dan menyatakan sikap perang.
Kediaman Pangeran Diponegoro di Tegalrejo menjadi saksi bisu perjuangan Pangeran Diponegoro melawan penjajah. Saat ini, kediaman Pangeran Diponegoro diubah menjadi Museum Sasana Wiratama. Di Museum tersebut dibangun dengan bertujuan untuk mengenang sosok dan Perjuangan Pangeran Diponegoro sekaligus juga untuk menyimpan benda-benda peninggalan yang berkaitan dengan Pangeran Diponegoro.